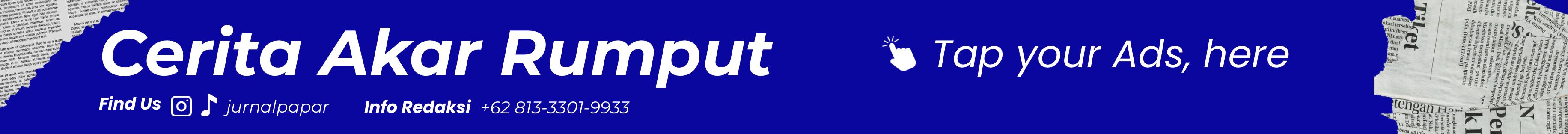PAPAR - Setiap kali tanggal 30 September tiba, bangsa Indonesia seperti dipaksa menengok kembali satu babak paling kelam dalam sejarahnya: tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965 yang dikenal sebagai G30S/PKI.
Pada tahun itu, usia Republik Indonesia baru menginjak dua dekade—baru saja lepas dari belenggu penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad. Namun, dalam situasi politik yang belum benar-benar stabil, gelombang besar kekacauan melanda. Enam jenderal TNI dan satu perwira menjadi korban kekejaman yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit. Bahkan Ade Irma Suryani, putri kecil Jenderal AH Nasution yang baru berusia lima tahun, turut menjadi korban keganasan peluru.
Nama-nama seperti Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, hingga ajudan Nasution, Lettu Pierre Andreas Tendean, tercatat sebagai pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini.
Lima puluh sembilan tahun kemudian, peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di ruang keluarga dan institusi pendidikan, tapi juga di ranah akademik dan kebudayaan.
Salah satu suara yang menyoroti pentingnya pemahaman utuh tentang peristiwa ini datang dari Tuban. Sudjarwoto Tjondronegoro, budayawan sekaligus pemerhati sejarah yang juga aktif di dunia akademik, menyampaikan pandangannya. Ia menilai, memahami G30S/PKI tak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong.
“Memahami G30S tidak boleh sepenggal-sepenggal, tapi harus sebagai sebuah keutuhan. Bagaimana kita melihat peristiwa ini dari kacamata pemerintah saat itu, posisi PKI, hingga peran TNI. Semuanya harus dicari kejelasan yang original,” tegas Jarwoto dalam wawancara dengan awak media.
Sudjarwoto juga menyoroti salah satu produk budaya yang sejak Orde Baru digunakan untuk membingkai narasi tragedi ini: film Pengkhianatan G30S/PKI. Menurutnya, film ini perlu direvisi karena mengandung banyak ilustrasi dramatis yang tak sesuai dengan format dokumenter.
“Film itu seharusnya dokumenter. Tapi yang terjadi adalah dramatisasi berlebihan yang justru mengaburkan kebenaran. Kalau mau menggugah semangat agar tragedi tak terulang, ya harus jujur dan obyektif,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa film tersebut lebih merepresentasikan kepentingan politik penguasa saat itu ketimbang menjadi media pembelajaran sejarah. “Film itu menyiratkan PKI memberontak seakan-akan dengan sendirinya. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, dalam setiap pemberontakan pasti ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat. Politik dan militer, dua-duanya tidak bisa dilepaskan dari dinamika itu,” jelasnya.
Sudjarwoto mengajak masyarakat untuk tidak berhenti di permukaan. Ia menyarankan agar tragedi G30S/PKI dipelajari secara kritis dan menyeluruh, termasuk menelaah keterlibatan aktor-aktor politik dan militer yang kala itu punya pengaruh besar terhadap arah negara.
“Sejarah tidak berdiri di ruang hampa. PKI memberontak itu fakta. Tapi mengapa mereka memberontak? Apakah semua kader PKI terlibat? Atau hanya sebagian? Apakah ada aktor militer lain yang bermain di balik layar? Itu semua perlu dijawab secara jujur,” pungkasnya.
Kini, di tengah era keterbukaan informasi dan teknologi, generasi muda punya peluang lebih besar untuk melihat sejarah dengan perspektif lebih luas. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi agar peristiwa seperti G30S/PKI tidak terulang kembali di bumi pertiwi ini.
Tag
Berita Terkait

Kunjungan Bersejarah ke Bojonegoro Batal, Presiden Prabowo Ungkap Penyesalan dan Minta Maaf

Diteror Bom, Pesawat Saudi Airlines yang Bawa Jamaah Haji Kolter 33 Asal Surabaya Mendarat Darurat

Dugaan Korupsi Dana Hibah Memanas! KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah dan Legislator dari PKB

Ada Bantuan Uang Rp600 Ribu dari Pemerintah yang Bakal Cair Juni 2025, Pekerja Non-ASN Buruan Cek!

Usulan Hari Kebudayaan Nasional Tuai Pro dan Kontra, DPD RI Gelar FGD Serap Aspirasi Masyarakat

Duel Krusial! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kabar Baik! PLN Kembali Beri Diskon Listrik 50 Persen Juni–Juli 2025, Hanya Pelanggan ini yang Dapat

Kejurnas Angkat Besi Senior 2025, Komitmen Petrokimia Gresik Dukung Prestasi Olahraga Nasional
Tag
Arsip
Berita Populer & Terbaru






































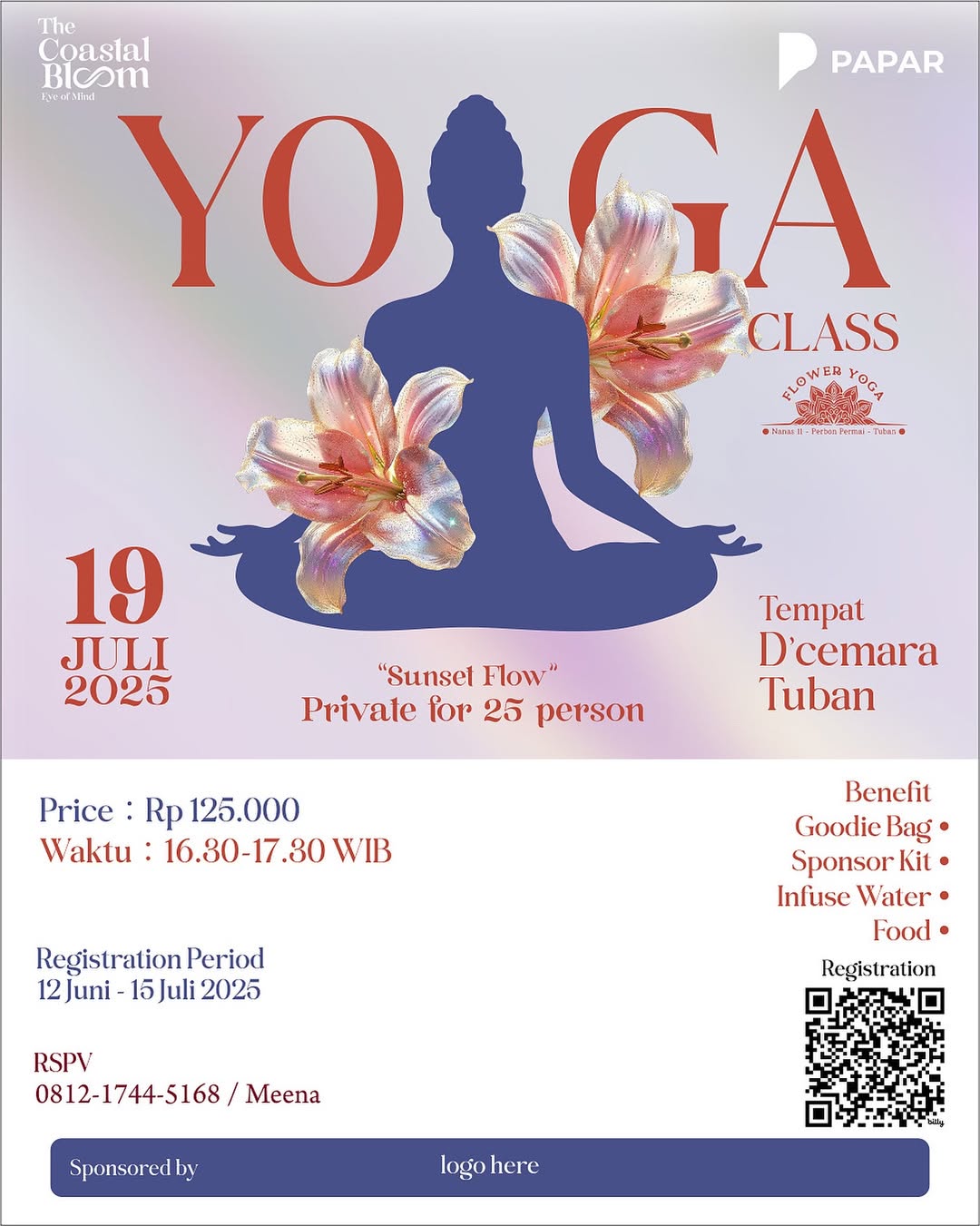

















































































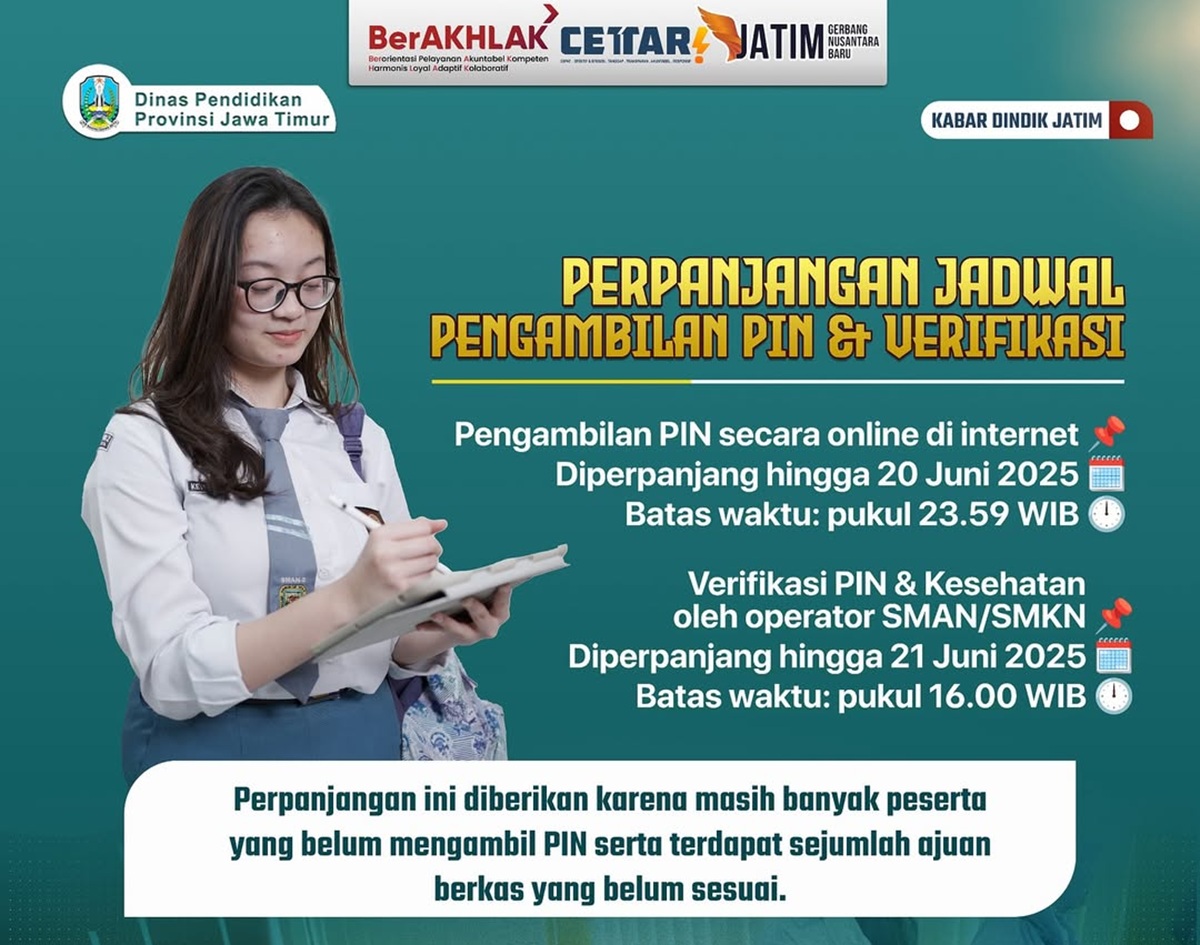










































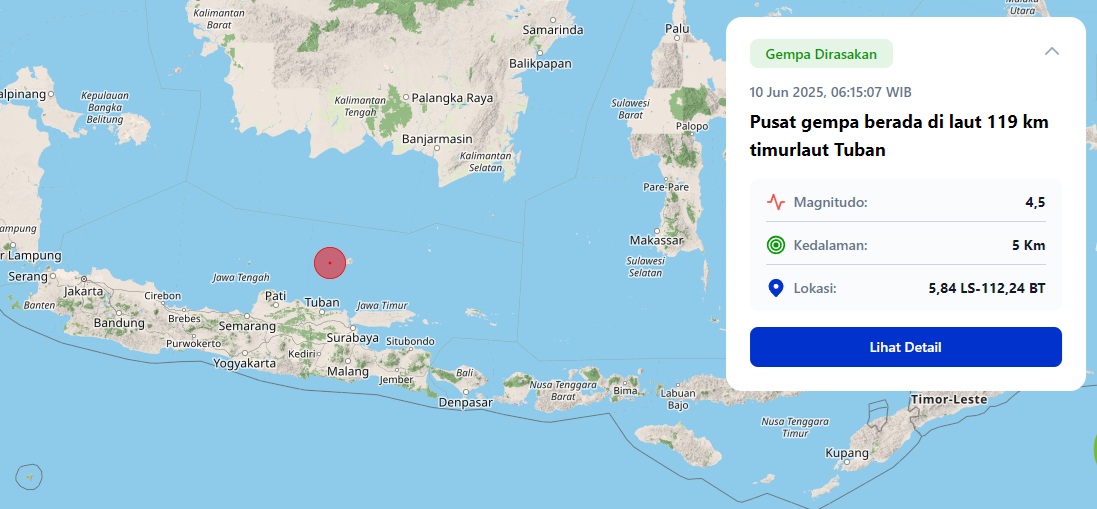













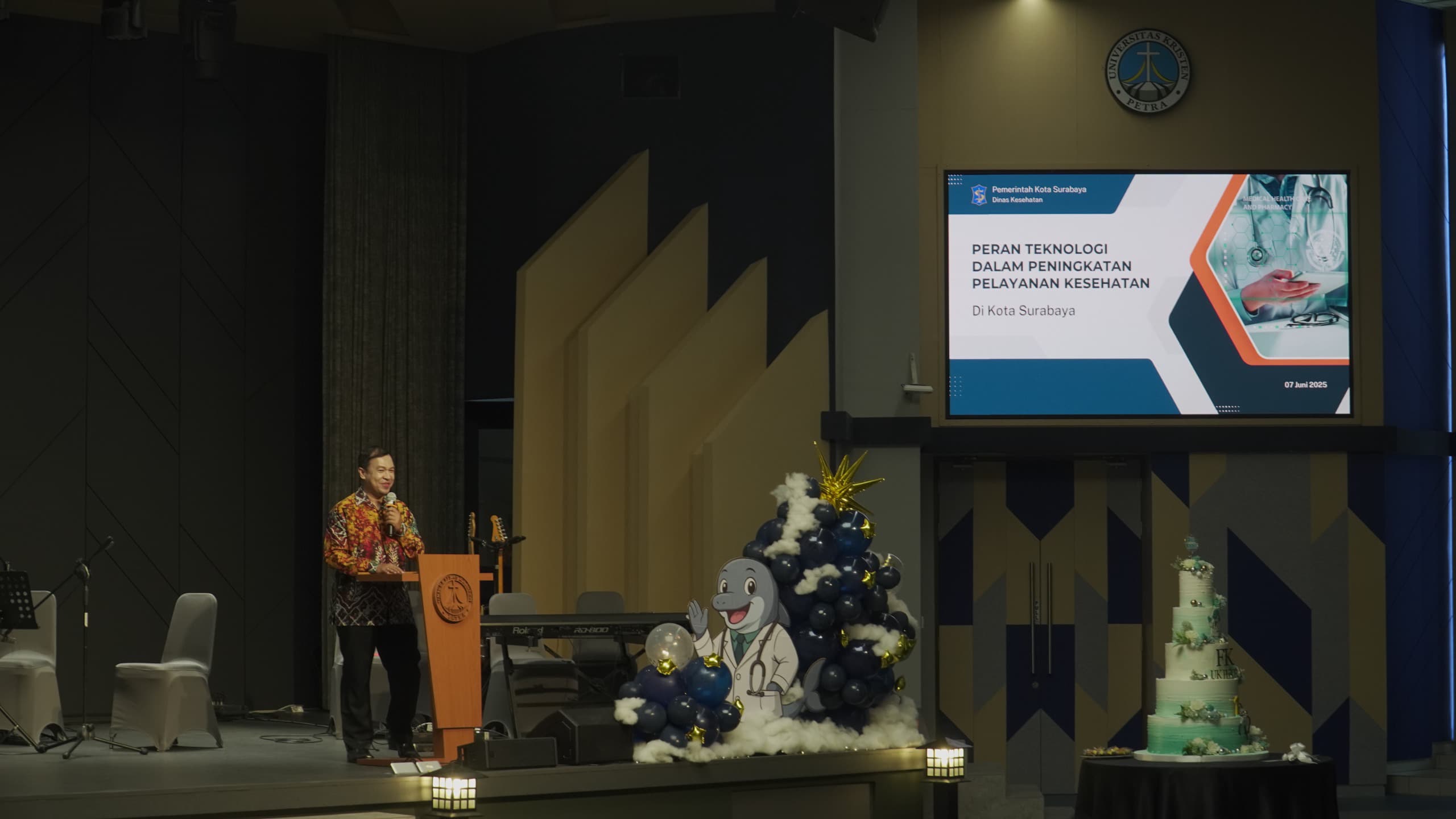

















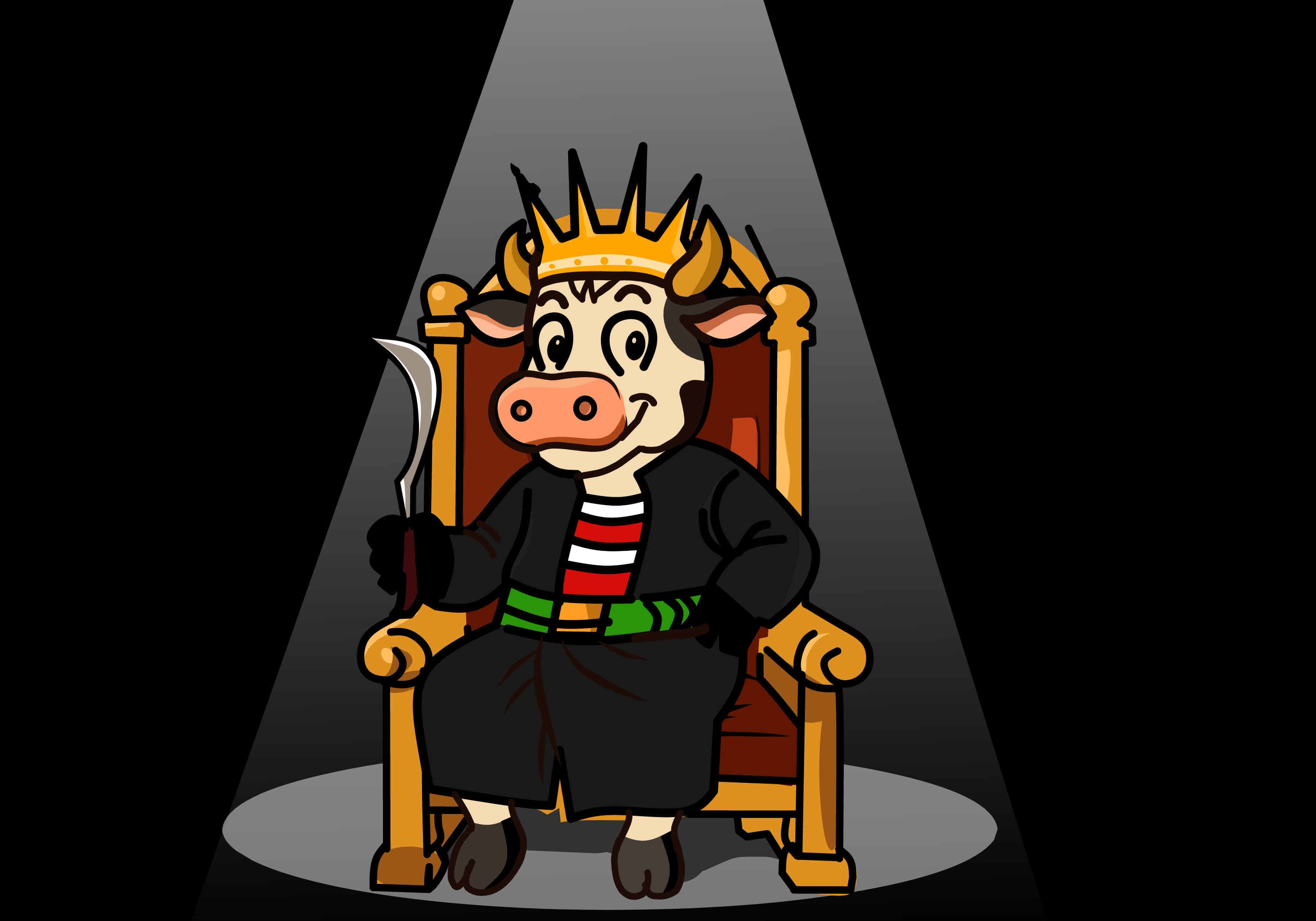























































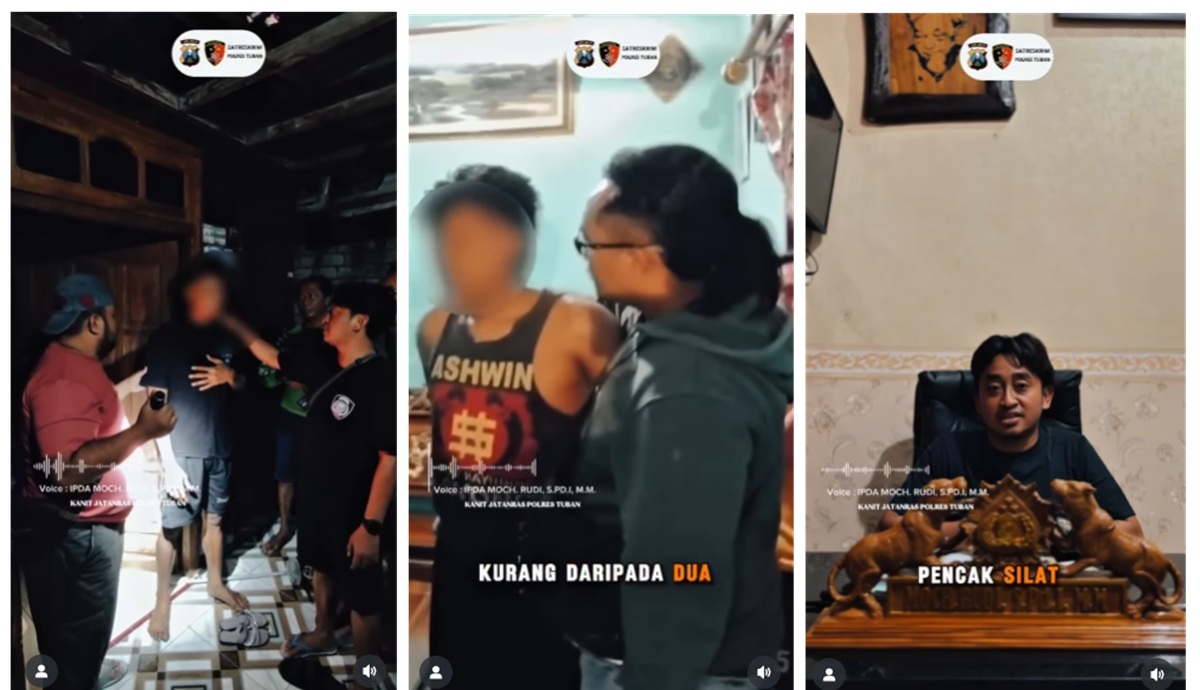


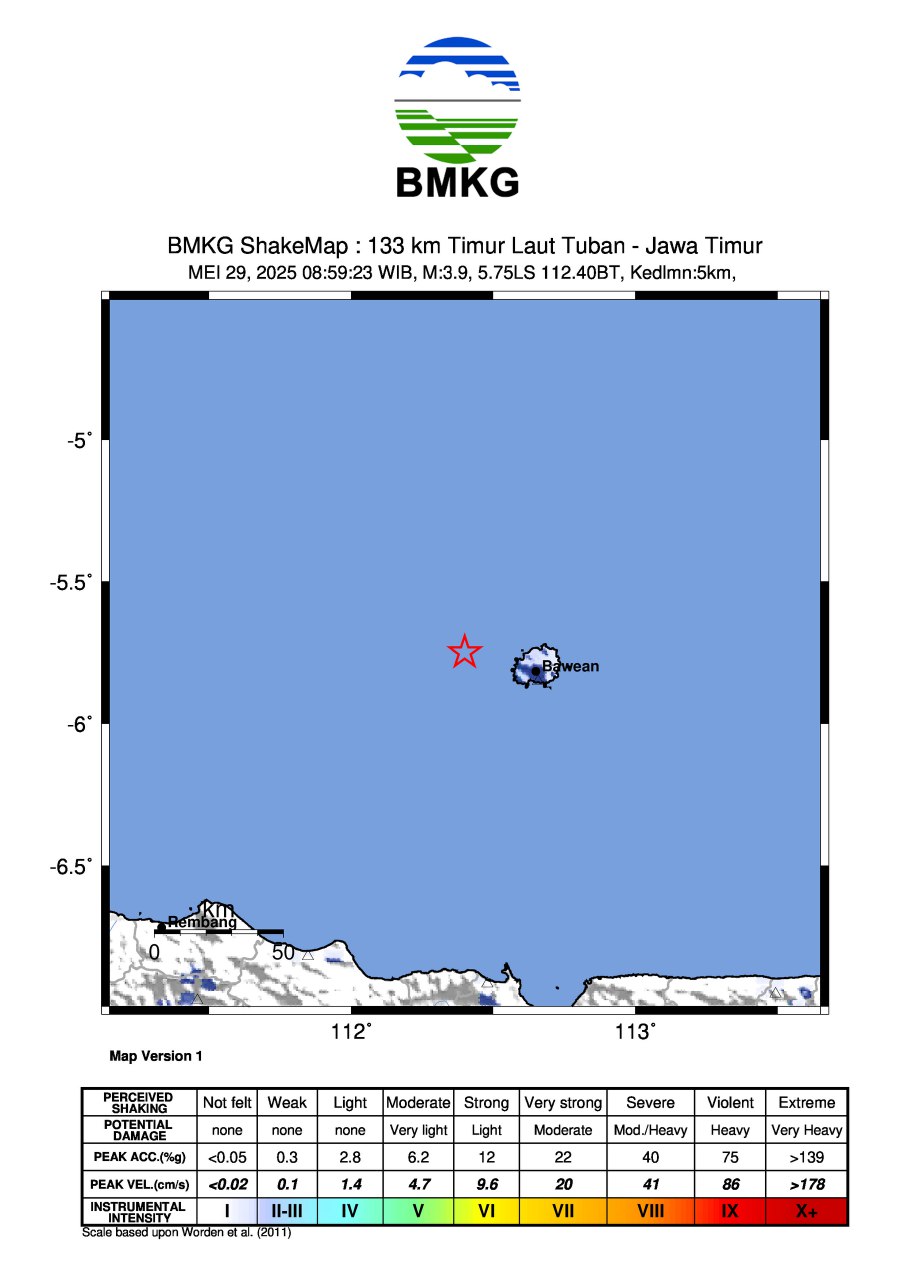



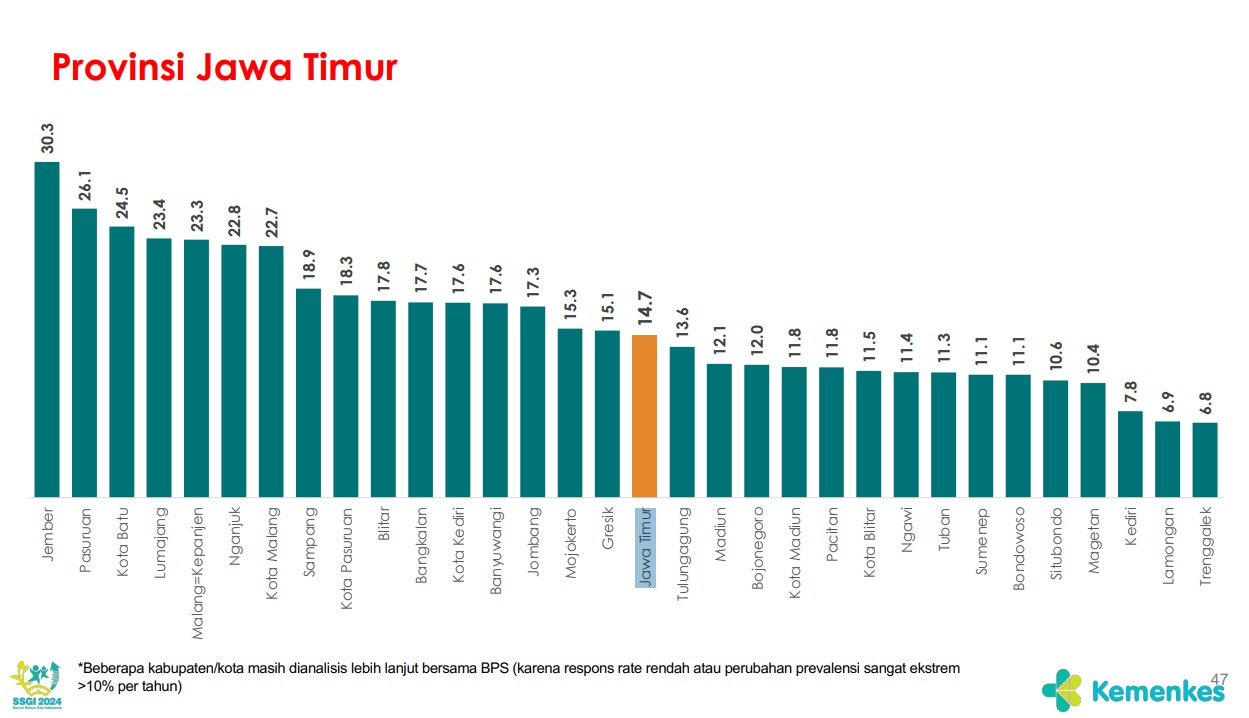



















































































































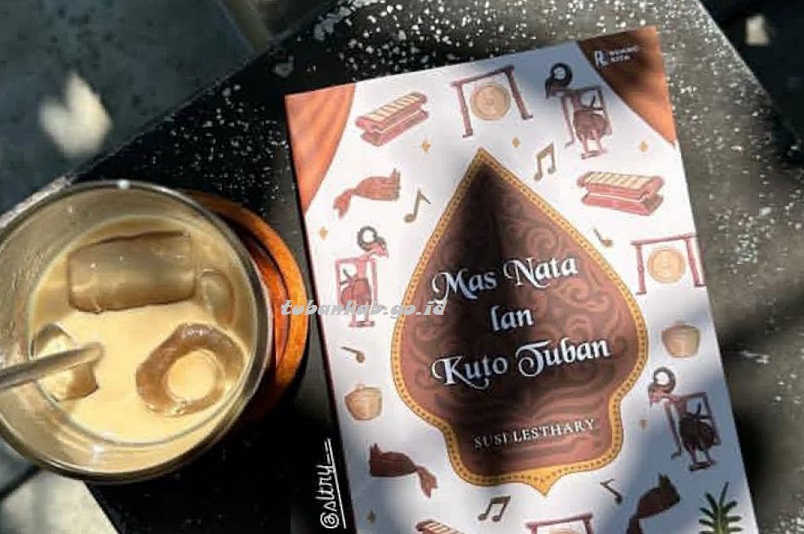






































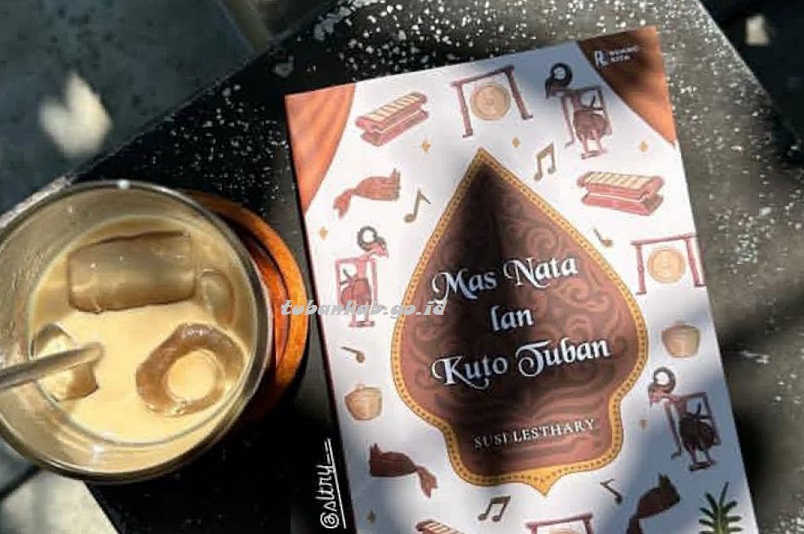


















































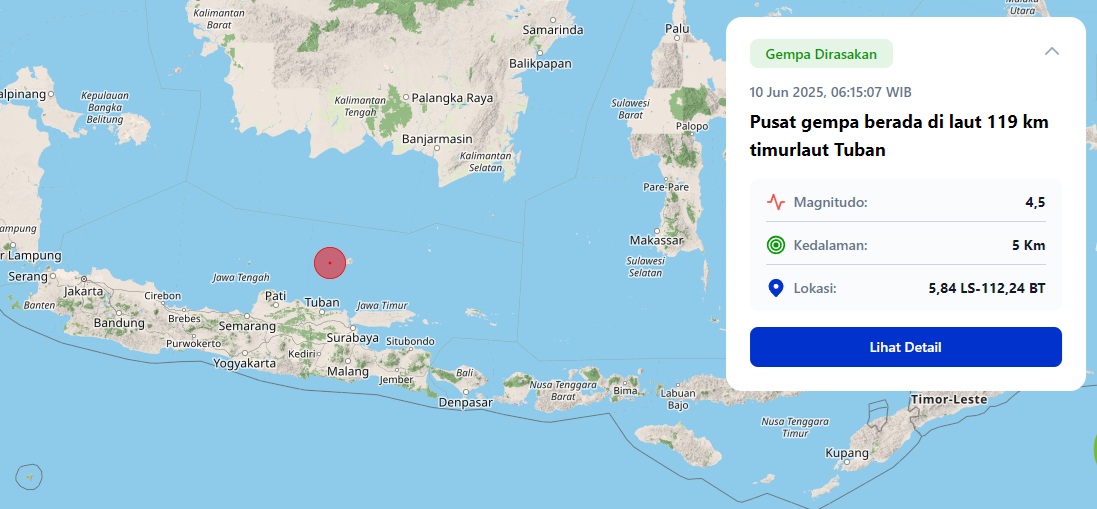












































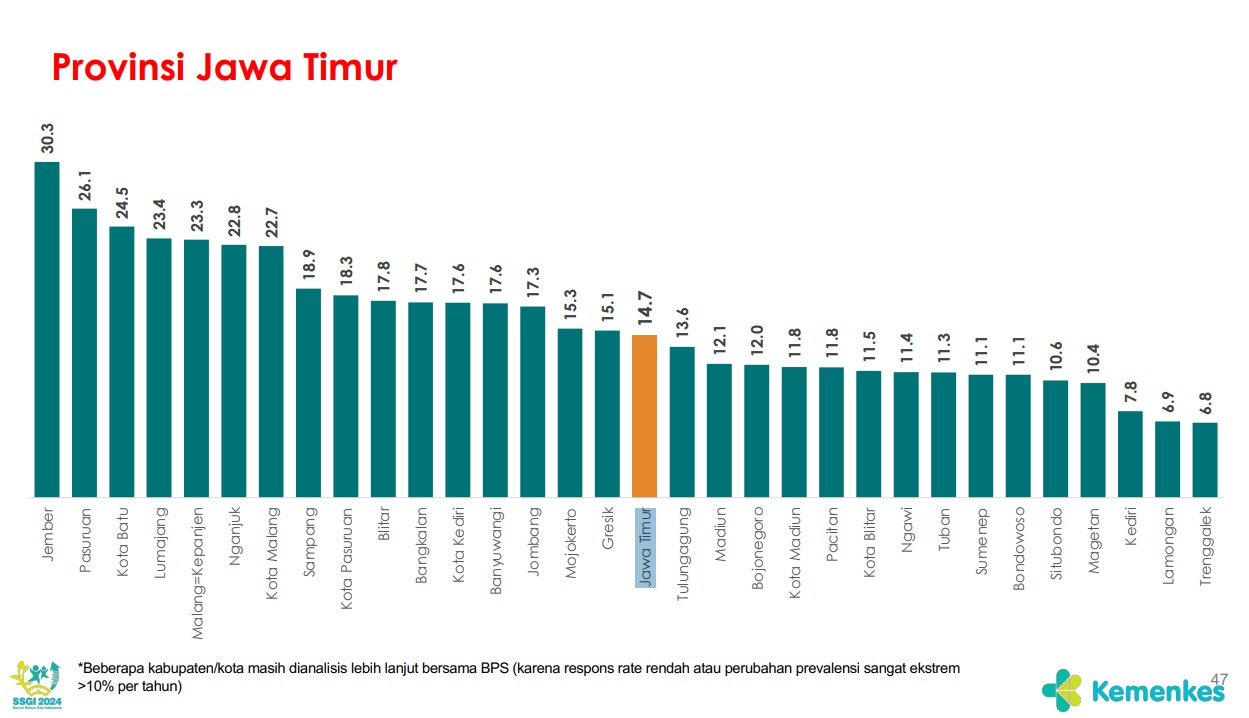










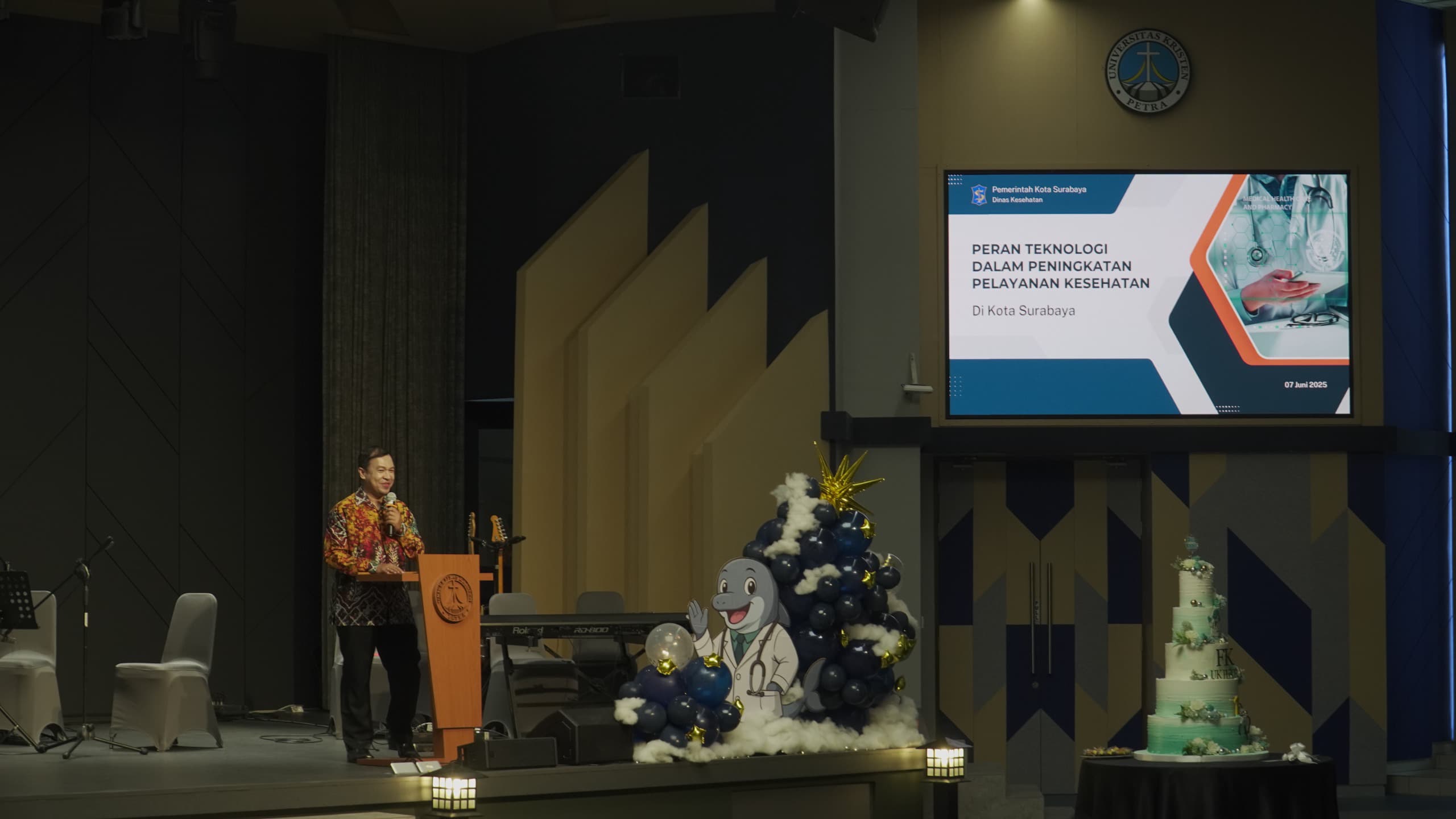














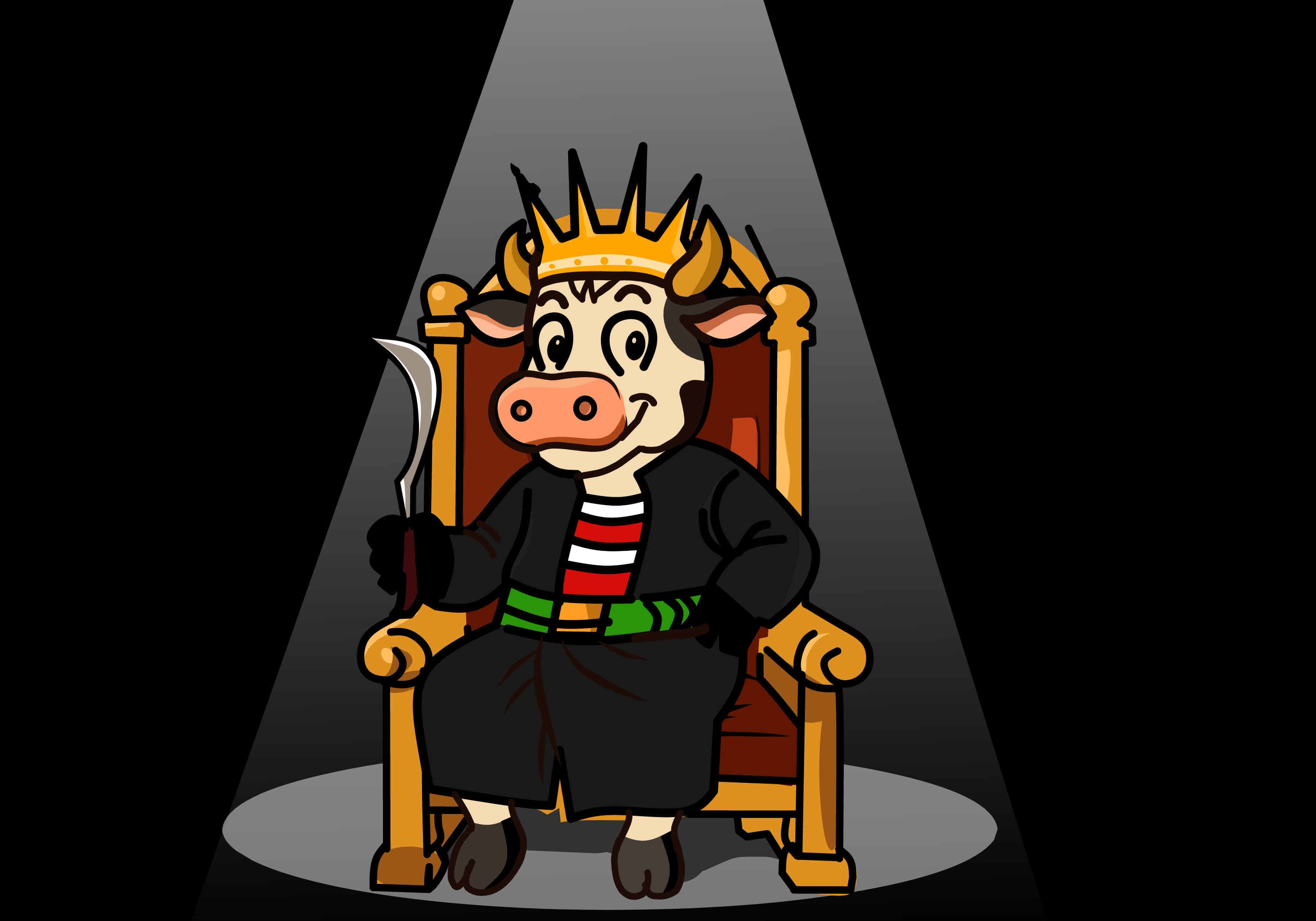




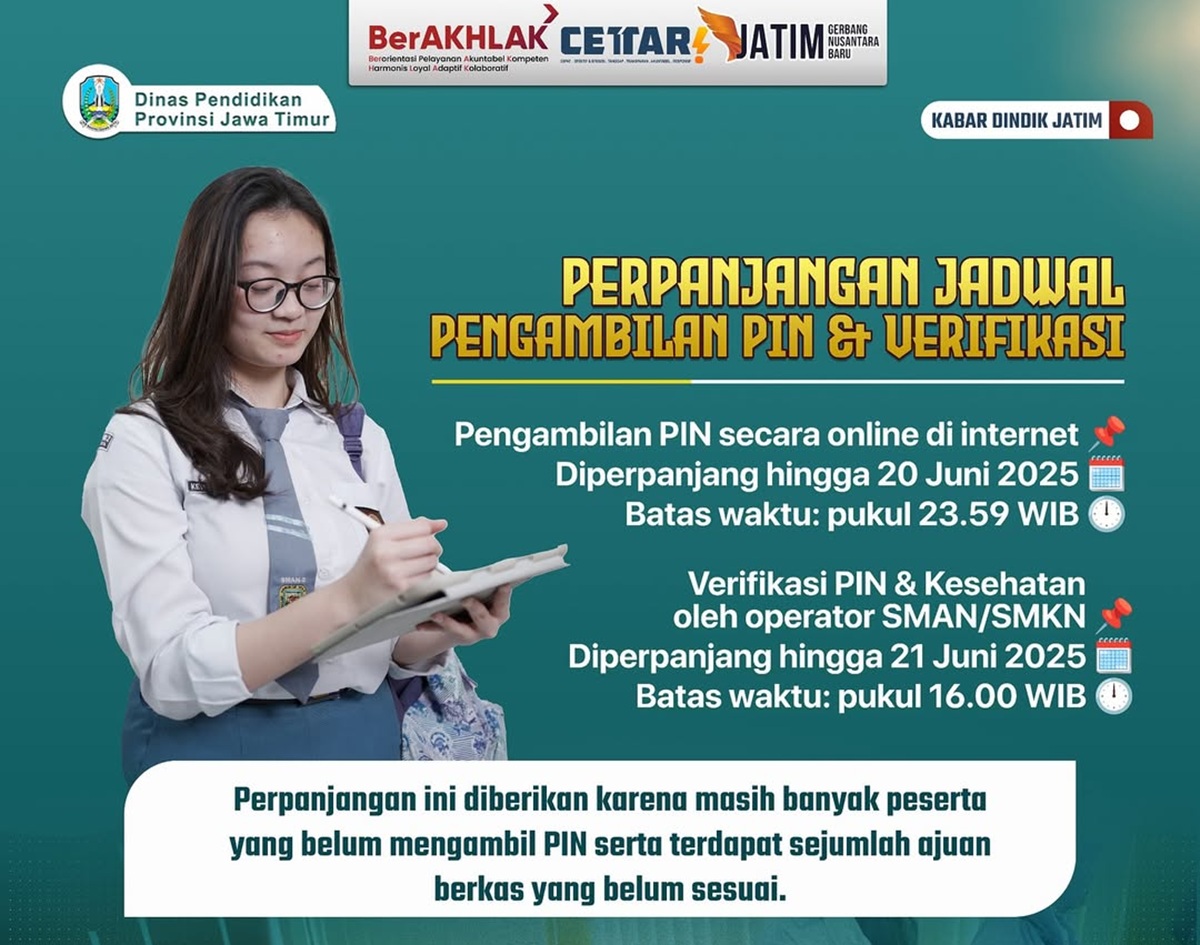



































































































































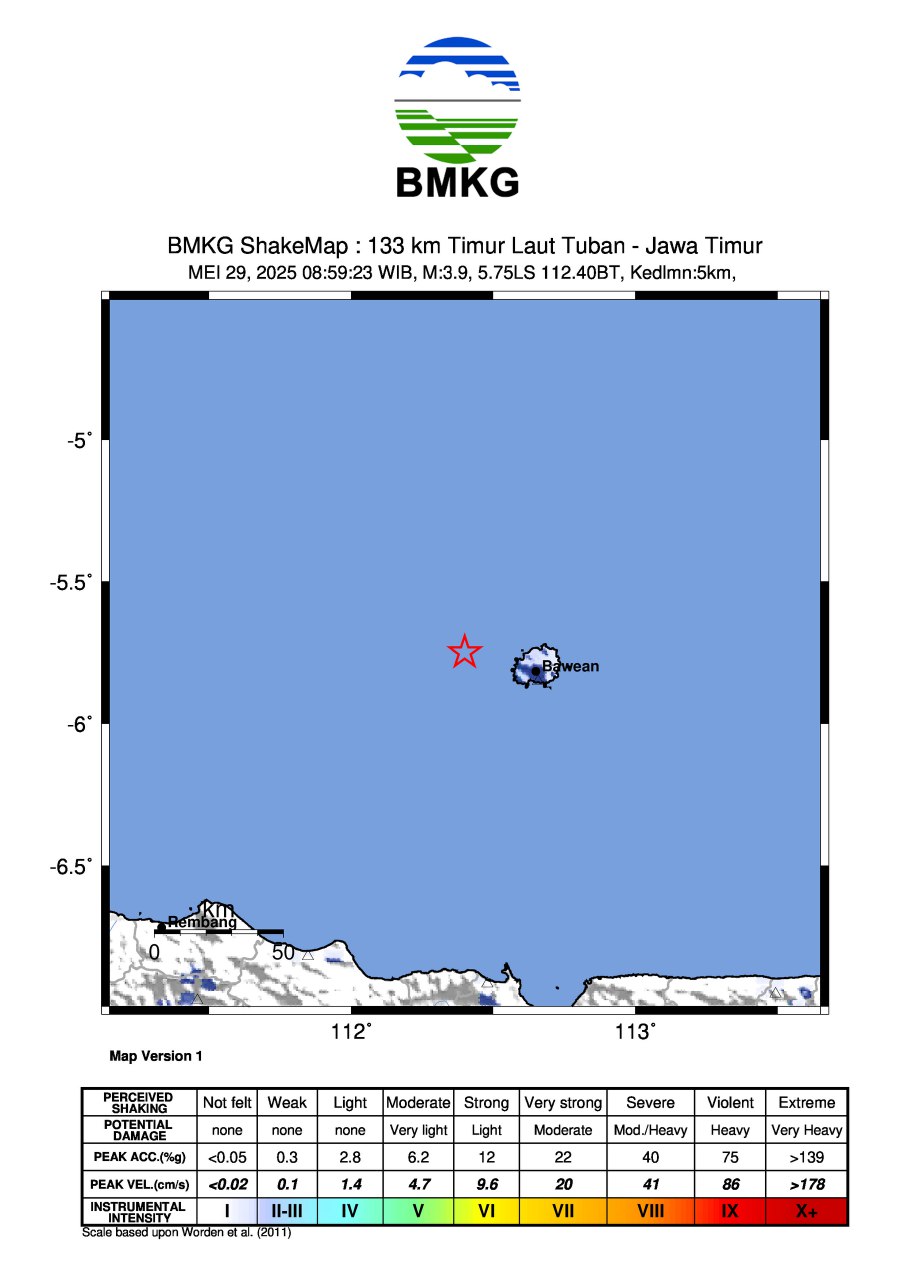





















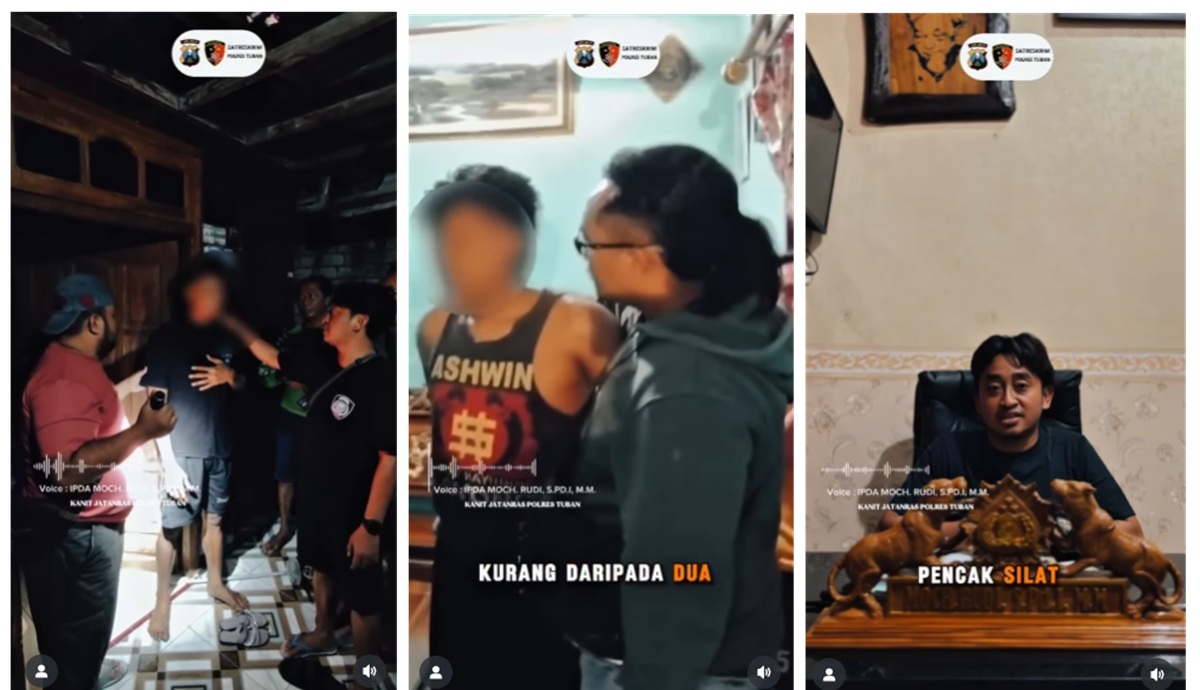




























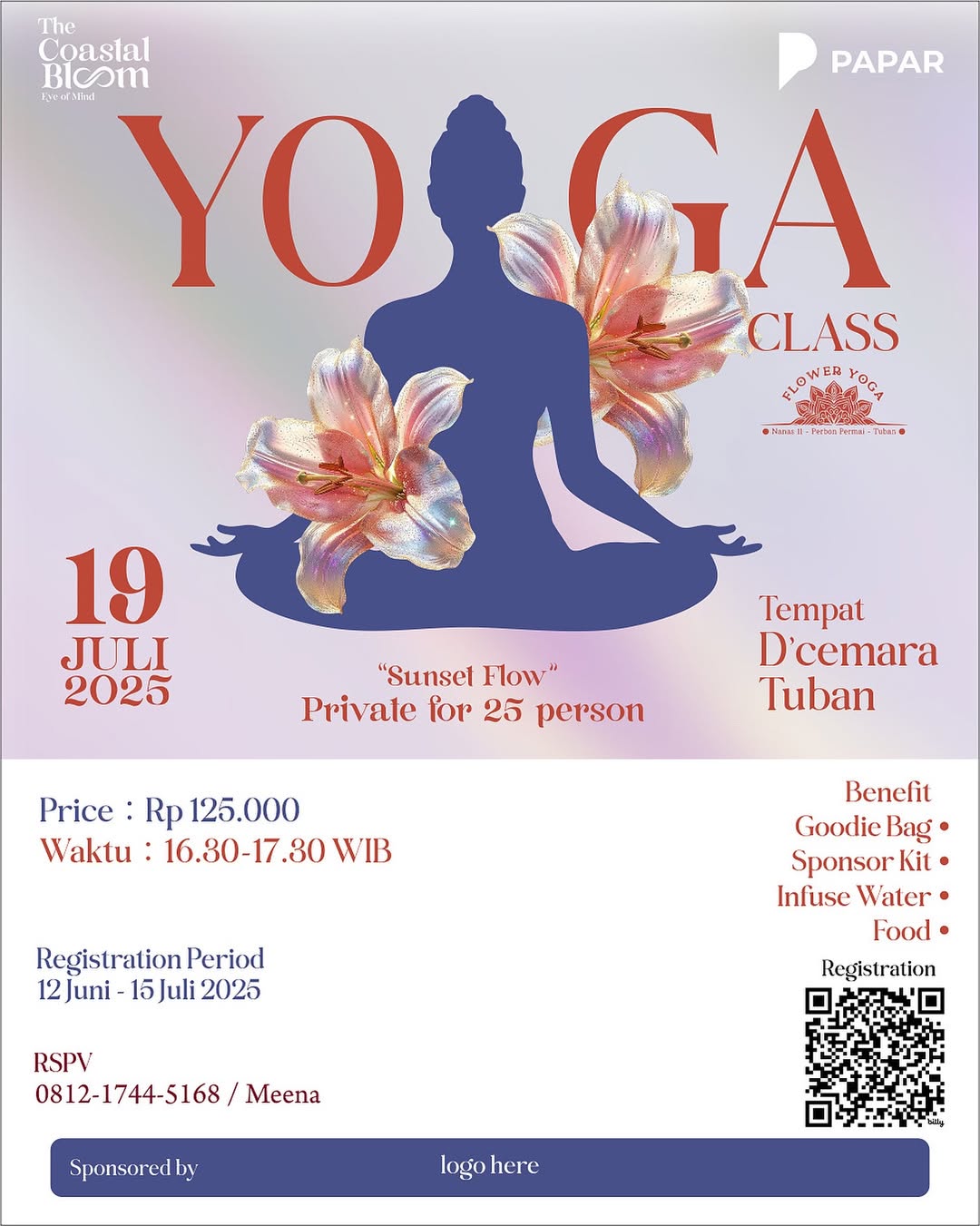




































Polling Online
Tidak ada polling tersedia.