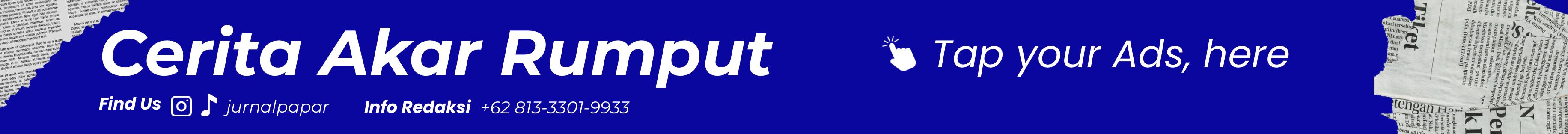PAPAR- Siang itu, Desa Karang masih basah. Bukan karena hujan, tapi karena embun dan lumpur yang belum sempat mengering. Di salah satu sudut desa yang tenang di Kecamatan Semanding, Tuban itu, terdengar suara ‘plek-plek’ pelan, berirama, mengisi udara siang yang wening.
Itulah suara tangan manusia yang menampar-nampar tanah liat. Di kota, itu mungkin dianggap aneh. Tapi di sini, itu pertanda hidup. Tanda bahwa perut akan terisi hari itu.
Dan di situlah saya bertemu Gendok.
Gendok bukan nama orang. Ia juga bukan nama hewan peliharaan. Tapi orang Tuban tahu: Gendok adalah benda sakral di dapur orang Jawa. Bentuknya sederhana: bundar, berlubang, kasar. Tapi justru karena kesederhanaannya itu, ia bertahan. Sudah puluhan tahun. Bahkan mungkin ratusan.
Dan di balik Gendok, ada tangan-tangan yang tak pernah menyerah.
Saya temui Ibu Sri siang itu. Tangannya penuh tanah. Kerut di wajahnya tidak bisa menipu: dia sudah lebih dari 20 tahun berurusan dengan tanah liat. Tapi ketika dia bicara tentang Gendok, matanya berbinar.
“Kalau tanah liatnya bagus, bisa sampai 200 biji sehari, Mas,” katanya sambil tersenyum. “Tapi sekarang, mendung terus. Ya, paling 50-an saja.”
Harga satu Gendok? Seribu lima ratus rupiah. Iya, cuma itu. Kurang dari harga sebungkus gorengan di kota. Tapi proses membuatnya? Panjang. Mulai dari mengayak tanah, mengaduk air, menamparnya sampai halus, lalu mencetaknya satu-satu. Belum lagi menjemur, membakar, dan menjaga api agar tak terlalu besar atau terlalu kecil.
Karena kalau api terlalu panas: Gendok bisa retak. Kalau terlalu lembek: tidak bisa dipakai.
Itu bukan sekadar produksi. Itu seni.
Tapi seni ini sedang sekarat.
Bukan karena kualitasnya menurun. Bukan. Tapi karena anak-anak muda mulai menjauh. Kota menawarkan gaji UMR dan AC. Desa hanya bisa memberi tanah liat dan debu.
Padahal, kalau dipikir, dari tanah liat itu, Ibu Sri bisa beli beras, bayar listrik, bahkan menyekolahkan anak.
Namun waktu terus berubah. Stainless steel dan plastik mulai masuk dapur-dapur. Ikan pindang pun kini lebih sering ditaruh di kotak plastik. Gendok mulai ditinggal. Perlahan. Diam-diam.
Tapi saya percaya: selama masih ada api di tungku, dan tanah di sawah, Gendok akan tetap hidup. Ia tidak butuh pamflet pemerintah atau selebrasi kementerian. Ia hanya butuh dihargai.
Mungkin lewat digitalisasi. Lewat media sosial. Lewat pasar daring. Atau cukup lewat tulisan ini.
Karena Gendok bukan sekadar barang. Ia adalah napas panjang sebuah budaya. Ia adalah bukti bahwa sesuatu yang lahir dari tanah, bisa lebih abadi dari beton.
Dan selama masih ada suara “plek-plek” di pagi hingga siang hari, Desa Karang masih punya harapan.
Berita Terkait

Merasa tak Dihargai, Anak di Tuban Kepruk Ayah Kandungnya dengan Batu, Begini Pengakuan Tersangka
Tag
Arsip
Berita Populer & Terbaru































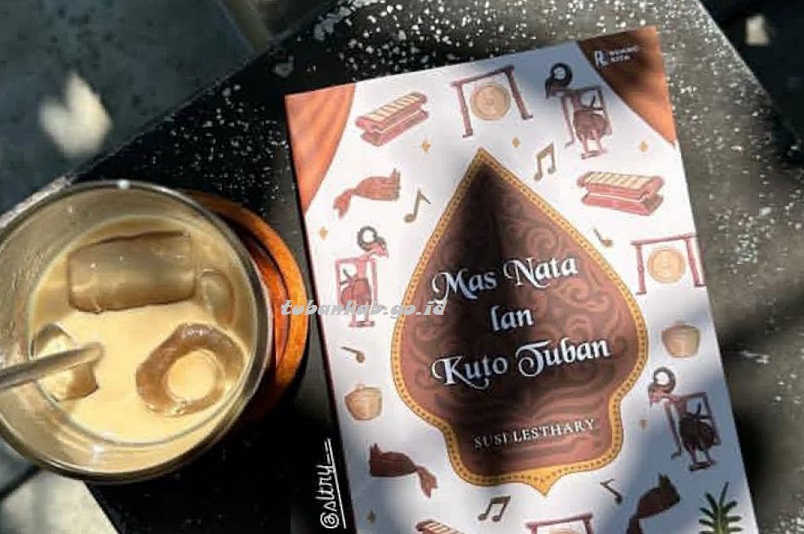



















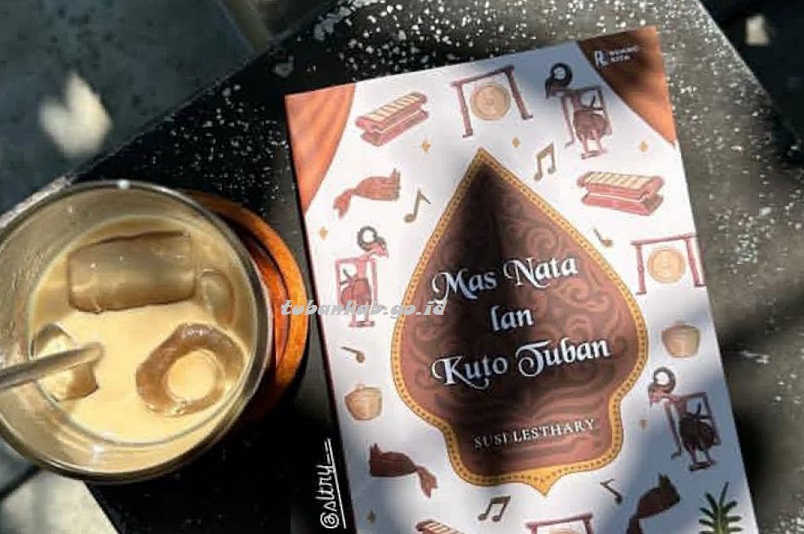






















Polling Online
Tidak ada polling tersedia.